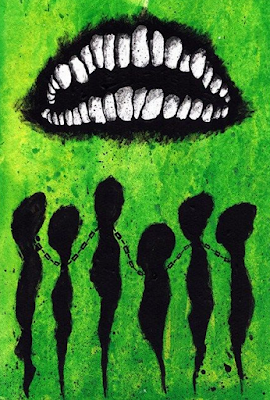Ada banyak cara untuk menghemat energi. Salah satunya, menonton anime. Aku tiduran pada bantal yang kutekuk menjadi dua. Aku menekuk bantal karena itu barang sudah kempes. Jadi, bisa kalian ketahui intensitasku dalam
Kali
ini Hinamatsuri. Anime absurd yang
bikin ngakak so hard. Aku tahu jika
lelucon itu relatif, tapi jika kotak tertawamu tak terganggu minimal dirimu
akan tersenyum. Bahkan Ndoro yang tak begitu suka anime direwangi nonton. Hana, anak manusia super yang berasal dari antah
berantah hidup bersama dengan seorang mafia jomblo bernama Nitta. Ceritanya
menggelinding begitu saja dengan para tokoh yang unik dan kocak.
Ada
banyak pesan dan kisah dalam anime ini, kadang mengharukan, menyebalkan, dan
tentunya jenaka. Ada episode lucu ketika keluarga Nitta mempertanyakan “siapa
Hana?” Berbagai upaya dilakukan untuk menjelaskan siapa Hana, tetapi tentu saja
ia tak tahu. Penonton saja tak tahu siapa si Hana. Daripada rumit dan banyak
akting, akhirnya si Nitta memiliki solusi terakhir.
Episode itu seperti mengingatkanku pada kisah Walid bin al-Mugirah (ayahnya Khalid). Bahkan ada sekitar 104 ayat Al Qur’an yang berhubungan dengan si Walid. Ada salah satu kisah lucu perihal ini yang kuingat. Si Walid yang pesohor kaum Quraisy tahu dan seorang sastrawan paham bahwa Al Qur’an bukan buatan manusia, tapi dirinya ingkar.
Pada
surat Al Qalam: 10-16, si Walid disifati aibnya oleh Al-Qur’an dengan sepuluh
sifat. Sembilan sifat itu diakuinya, tapi ada sifat yang tidak ia mengerti dan
membuatnya marah, yaitu kata zanim. Zanim memiliki arti mengaku-ngaku nasab
atau nasabnya tidak jelas atau lahir sebagai anak zina. Tentu saja hal ini
berkebalikan dengan yang sering Walid gaungkan sebagai keluarga Quraisy
terhormat dan memiliki kedudukan yang tinggi. Satu kata itulah yang membuatnya
marah dan mendatangi ibunya.
"Bu, Al Qur'annya Muhammad menyifatiku sepuluh hal. Sembilannya saya akui itu, tapi ada satu yang mengganjal: zanim. Muhammad tidak mungkin bohong soal ini. Saiki, Ibu cerita yang sebenarnya kalau tidak pedang ini bisa menebas lehermu." Sambil mengancam membunuh ibunya, secara tidak langsung ia mengakui kesembilan sifat yang melekat dalam dirinya.
Ibunya pun berkata, "Ngene lho le, bapakmu kuwi impoten, pada satu sisi memiliki harta yang banyak, dari keluarga terpandang, di sisi lain ya butuh keturunan. Akhirnya, ibu melakukannya dengan seorang penggembala. Yo, tukang angon kuwi bapak aslimu."
"Bu, Al Qur'annya Muhammad menyifatiku sepuluh hal. Sembilannya saya akui itu, tapi ada satu yang mengganjal: zanim. Muhammad tidak mungkin bohong soal ini. Saiki, Ibu cerita yang sebenarnya kalau tidak pedang ini bisa menebas lehermu." Sambil mengancam membunuh ibunya, secara tidak langsung ia mengakui kesembilan sifat yang melekat dalam dirinya.
Ibunya pun berkata, "Ngene lho le, bapakmu kuwi impoten, pada satu sisi memiliki harta yang banyak, dari keluarga terpandang, di sisi lain ya butuh keturunan. Akhirnya, ibu melakukannya dengan seorang penggembala. Yo, tukang angon kuwi bapak aslimu."
Kurang
lebih seperti aku mengingat kisahnya. Terasa aneh jika seseorang mengakui
kehebatan Al Qur’an, tapi ingkar. Ini menandakan bahwa Al Qur’an pada dasarnya
dapat dengan mudah dipahami oleh siapa saja, bahkan orang kafir. Jadi, kelak tak ada alasan manusia di hadapan Allah tidak paham risalah Ketuhanan. Lantas mengapa
mereka menolaknya? Mungkin ada sesuatu yang menghalangi. Jawabannya bisa
beragam. Salah satunya adalah keangkuhan.
Keangkuhan
pula yang membuat azazil terusir dari kedudukannya. Perihal ini banyak orang
membuat tafsir mengenai keimanan azazil pada Tuhan dan blablabla. Namun, tiap
kali aku bertanya, “mengapa dirimu tidak menjadi pengikutnya azazil atau iblis
saja? Tak perlu sholat, zakat, atau puasa. Hidup bisa sesuka hatimu dan bebas
hukum.” Tetapi, mereka tidak mau atau menolak. Mereka mengaku masih mencintai
Rasulullah, dan sayang sekali tidak pernah kudengarkan mereka mengisahkan kehebatan
Rasulullah. Kapan-kapan aku ceritakan kerennya Rasulullah.
Aku
sering memikirkan ini, kata orang-orang aku itu baik meski agak sinting, tetapi
aku tak sebaik itu. Yah, aku kelihatan baik karena Allah telah menjaga aibku. Tentunya,
aku tak berharap memiliki nasib senahas karakter David Lurie nya Coetzee. Ah,
menjadi seorang kriminal bukanlah hal yang memalukan. Tetap menjadi penjahat
itulah aib yang memalukan.
Nani kore?
Gohan...
Si
Hana membuat perutku lapar, tapi kok ya ngantuk.