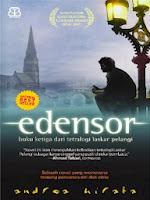I am
A little bit of loneliness
A little bit of disregard
A handful of complaints
But I can't help the fact
That everyone can see these scars
(Faint – Linkin
Park)
Sebelum anda melanjutkan membaca artikel ini, hendaknya anda memutar lagu Faint dari Linkin Park (jikalau belum memilikinya sebaiknya anda mengunduhnya). Memang tidak ada kaitannya antara Linkin Park dengan petapa. Setidaknya itu dapat mengurangi kejenuhan atas pemberitaan yang membentuk energi negatif.
Dulu. Dulu sekali saya (yang lain)
pernah menjadi seorang masokis, bukan masokis yang merupakan bentuk parafilia,
tetapi lebih pada penyimpangan psikologi untuk ingin dipenjara. Berawal dari
konklusi bahwa engkau tidak akan berpikir jernih untuk menulis suatu karya jika
tidak di dalam penjara. Ketika para koruptor ketakutan akan penjara dan
kriminal lain lari dari jeratan hukum, saya malah ingin merasakannya. Liberte!!! Suatu teriakan dari gema
revolusi Perancis yang bertahan sampai saat ini, dan kini terdiam di Amerika
Serikat menjadi sebuah patung. Dan kini terekam dalam buku dan hati para
manusia dengan baik. Penjara merupakan kekuatan tersendiri untuk membangunkan
tingkat imajinasi dan keluasan mata dalam memandang. Dari dalam jeruji besi
semua nampak lebih jujur, meskipun nampak kotor. Namun, itu lebih baik
dibandingkan kemunafikan yang telah memoles rupanya dengan keramahan dan
keteraturan yang dipaksakan. Di sana saya bisa menjadi petapa yang menyepi,
diam, dan tidak terlihat. Mataku bisa berubah menjadi mata elang yang luas
memandang. Kemudian menjadi cacing yang berpandangan sempit yang melihat segala
sesuatu menjadi serba besar. Kesakitan membuatku semakin bergairah. Itu tidak
lazim memang, tetapi seperti kata Foucault bahwa setiap zaman memiliki definisi
kegilaannya sendiri. Definisi kegilaan yang berubah sebagai indikator
terjadinya perubahan paradigma, dimana Capra menyebutnya sebagai bagian dari
titik balik peradaban.
“Dari penjara itu engkau akan
membuat berbagai karya yang menggemparkan,” ujarku (yang lain) pada saat itu.
“Tetralogi Pulau Buru (Pramoedya
Ananta Toer), Catatan-Catatan dari Penjara (Gramsci), Dari Penjara ke Penjara
(Tan Malaka), Don Quixote (Miguel de Cervantes), Fi-Zhilalil Qur’an (Sayyid
Qutb), Pledoi Indonesia Menggugat
(Soekarno). Masih belum puas aku memberikan contoh karya dari penjara? Hitler
pun dengan Mein Kampf dan Abu Bakar Ba’asyir tidak ketinggalan.”
Aku terus mengoceh dengan mengutip
dari Ibnu Taimiyah, “Dan dipenjara yang sebenarnya
ialah yang dipenjarakan hawa nafsunya. Bila orang-orang yang memenjarakan saya
ini tahu bahawa saya dalam penjara ini merasa bahagia dan merasa merdeka, maka
merekapun akan dengki atas kemerdekaan saya ini, dan akhirnya mereka tentulah
mengeluarkan saya dari penjara ini.”
Lantas diriku yang lain mengambil
alih dengan keinginan menyendiri di gunung untuk menghindari kegilaan duniawi.
Penjara terlalu berisik dengan kenaifan pula. Kota terlalu cepat, penuh polusi
serta kemacetan. Di sana masing-masing memiliki Gatoloco yang berbeda topeng
berevolusi dengan halus: kalimat-kalimat bijak nan halus untuk pemerkosaan,
kondisi-kondisi pemaaf yang kompromis. Obsesi Nietzsche terhadap Zarathustra
menjadi Gatoloco bagi kaum ‘kiri’ yang membuat lebih skeptis dan apatis
terhadap realitas. Dunia menghasilkan ‘Si Gila’ Nietzche, ‘Sang pemberontak’
Camus, Hitler yang paranoia, dan narcissus baru di media sosial.
Secara duniawi tidak ada yang
bergaransi, semua membutuhkan resiko. Begitu juga Resi Bisma ketika
meninggalkan pertapaannya untuk turun gunung menjadi guru Pandawa dan Kurawa. Ia
tidak menyangka bila pesona kekayaan menjeratnya, itu pun diakuinya. Lantas,
apakah saya? Pertanyaan tersebut terus terjadi sampai para Gatoloco kelelahan
yang kemudian berlanjut dengan berkomplotnya iblis dan dajjal. Mereka muncul
dengan kebaikan, lalu coba menjerumuskan.
Banyak orang yang saya kenal dan
temui mengatakan sanggup menghadapi berbagai godaan. Pada mulanya saya
memercayai ucapannya karena intelektualitas mereka. Pemikiran bukanlah
berjenjang seperti dibilang Comte, melainkan utuh. Dari berpikir metafisik,
logis, dan afeksi. Memang terkadang pemikiran menghasilkan tindakan, namun
tidak selalu tindakan berasal dari pemikiran. Terdapat faktor-faktor yang
memengaruhi, seperti perasaan, situasi, spontanitas, afeksi, dan kemampuan.
Engkau perlu membangunnya. Tetapi,
perlu pemikiran jernih yang memandang segala sesuatu secara meluas dan hati
yang tenang, bukan melalui kegundahan dan pesimistis. Seperti banyak dialami
manusia masa kini. Diskotik yang selalu sesak; ekstasi yang penuh fantasi;
keriuhan sentuhan perkelaminan. Dunia beserta teorinya dibangun dengan
keputus-asaan. Pesimistis yang menghasilkan nihilisme. Tak akan engkau temukan
solusinya karena yang tersisa adalah pembenaran-pembenaran. Pemuka agama sudah
nyenyak. Semua tampak gonyah walaupun kelihatan kokoh. Tidak kah kau dapat
melihatnya?
Mereka akan terus lari. Mencari
ketenangan di pinggir laut dan di atas gunung. Mereka tidak akan menemukan
apapun. Sang Petapa sudah banyak yang turun gunung dan merapat pada keramaian
kota. Seperti halnya Musashi, Petapa perlu menghindar menyimpang di kesunyian
dan lalu bergerak maju untuk membunuh kegelisahan serta kelinglungan bagi
mereka yang mencarinya.
Banyak cara menjadi petapa. Paling
efektif adalah dengan menghindar menyimpang. Meskipun tidak ada jaminan untuk
menghilangkan permasalahan hidup, dan permasalahan itu adalah solusi bagi
manusia-manusia yang mencarinya. Hingga telinga sang petapa penuh kotoran
karena cerita-cerita.
Dan entah sejak kapan saya tidak
menyukai ‘kiri’ yang dulunya kupuja. Mungkin dogma akan dunia diciptakan dengan
struktur keseimbangan membuat kiri bergeser menjadi topangan rasio dalam
membangunkan hatiku. Kapan itu? Saya sendiri lupa.
Musik telah berganti dengan lagu Breaking the Habit karena lupa melakukan
repeat otomatis. Sampai pada lirik, I
don't want to be the one, the battles always choose.
Semarang, 30 Desember 2013