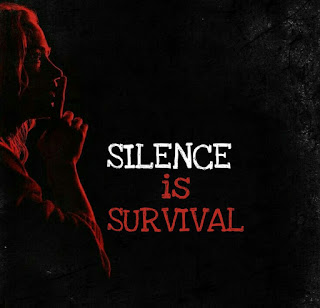Apa yang akan
kamu lakukan ketika ada yang berkata “Call
me Ishmael” saat membuka halaman pertama? Tentu saja hal ini tak lumrah
pada zaman dulu, seolah ada orang asing yang mengajakmu berbicara dan kamu akan
terus diajak dalam petualangannya dalam buku Moby Dick. Atau saat Kafka
mendobrak kesadaran dan mengagetkan kita dengan kalimat pembuka, “As Gregor Samsa awoke one morning from uneasy dreams he found himself
transformed in his bed into a gigantic insect.”
Pada suatu
karya kalimat pembuka menjadi sangat sakral karena akan memberikan kesan dan
kehendak membaca kalimat berikutnya. Akan tetapi, saya punya pendapat lain saat
Leila S. Chudori membuka novel Pulang:
“Dia muncul seperti selarik puisi yang
belum selesai.” Selain memberi nuansa misterius, kalimat tersebut terkesan
puitis. Leila memberikan diksi puitis untuk pembacanya. Pembuka tersebut
memenuhi keutamaan unsur diksi menurut Aristoteles: jelas dan tidak biasa. Ini
tentu tidak mudah dan tidak semua penulis mampu membuatnya. Saya kerap heran
bagaimana seseorang mampu menulis diksi puitis.
Konon, kalimat
puitis identik dengan puisi. Well, sejak
SD sampai sekarang puisi merupakan hal yang sulit kupahami sehingga saya hanya
mampu menikmati larik-larik puitis karya penyair, tanpa mampu membuatnya.
Mungkin, dulu bagiku, puisi hanya sekedar untaian kata untuk merayu wanita.
Dengarkanlah
puisi Neruda berjudul I Like for You to
be Still:
I like for you to be still
it is as though you are absent
And you hear me from far away
And my voice does not touch you
it seems as though your eyes had flown away
And it seems that a kiss had sealed your mouth
Atau Are You The New Person, Drawn Toward Me?
Milik Walt Whitman:
Are you the new person drawn toward me?
To begin with, take warning—I am surely far
different from what you suppose;
Do you suppose you will find in me your ideal?
Do you think it so easy to have me become your
lover?
Do you think the friendship of me would be
unalloy’d satisfaction?
Do you think I am trusty and faithful?
Do you see no further than this façade—this
smooth and tolerant manner of me?
Do you suppose yourself advancing on real
ground toward a real heroic man?
Have you no thought, O dreamer, that it may be
all maya, illusion?
Sebenarnya masih
banyak lagi soneta-soneta cinta Neruda, Whitman, atau Gibran. Maklum, ini pemahaman
dangkal seseorang yang tak mendalami puisi. Begitulah saya melihat puisi yang
selalu puitis, sehingga saya menulis puisi saat jatuh cinta. Dan itu bermula
dari nasihat seorang kawan,
“Koen, yen pengen dapat pacar: nulis puisi! Kirimi dia puisi pas
tengah malam.”
Saya yang tak
pernah tuntas menulis puisi sejak kecil kemudian mendadak latihan membuat
puisi. Meski nasihatnya terasa menyimpang dan terasa ganjil, tetap saja saya
menurutinya. Layaknya kalimat pembuka novel Pulang, puisi-puisiku jarang
selesai dan jikalau selesai kemudian menjadi puisi gelap. Walaupun begitu,
ternyata benar, resep itu manjur.
Lambat laun
saya pun menyadari bahwa tak semua puisi bernada puitis untuk lawan jenis. Kita
dapat melihat karya-karya Chairil atau Wiji Thukul yang lugas dan tajam. Mungkin
juga dengan... hmmm... gimana ya? Begini, apa yang terlintas dalam benakmu saat
mendengar kalimat “starving hysterical
naked”? Terkesan aneh dan membuat kita ingin tertawa, kan? Puisi Howl oleh Ginsberg mewakili karya-karya Beat Generation.
Sepulang dari
Jogja yang mampir dahulu ke Solo, selepas pengalaman-pengalaman emosional dan
spritual, kulihat puisi-puisiku yang lampau. Sesekali tersenyum kecil dan
geleng-geleng, dan tentunya banyak bertanya: apa maksud puisiku ini? Atau mengapa
aku menggunakan kata ini? Jejak rasa dalam puisiku itu seperti lindap, adakalanya saya seperti terputus dengan jejakku sendiri.
 Dahulu saya tak
paham maksud dari kata-kata Octavio Paz, “Like
a poem, it is not linear, it meanders and twists back on itself, shows us what
we do not see with our eyes, but in the eyes of our spirit.” Benar, apa
yang diperlihatkan puisi tak melalui mata lahiriah, melainkan penyelaman relung
–relung jiwa manusia. Dan saya telah kehilangan makna dari puisi yang belum terselesaikan. Apakah rasa dan ingatan saat itu sudah menguap sehingga tak mampu lagi kutelusuri?
Dahulu saya tak
paham maksud dari kata-kata Octavio Paz, “Like
a poem, it is not linear, it meanders and twists back on itself, shows us what
we do not see with our eyes, but in the eyes of our spirit.” Benar, apa
yang diperlihatkan puisi tak melalui mata lahiriah, melainkan penyelaman relung
–relung jiwa manusia. Dan saya telah kehilangan makna dari puisi yang belum terselesaikan. Apakah rasa dan ingatan saat itu sudah menguap sehingga tak mampu lagi kutelusuri? Entah siapa yang bilang, saya lupa, tetapi masih teringat betul kata-kata tersebut yang mengatakan, “Jika kamu tidak dapat menulis puisi, atau setidaknya tak mampu menikmatinya, berhati-hatilah karena itu menandakan hatimu keras.” Dan kusadari ternyata tugas penyair itu sulit karena menyampaikan perwakilan rasa dari jiwa manusia yang melampaui bahasa.
Pada
momen-momen tersebut saya bersyukur ternyata masih terdapat lilin kecil yang
menyala dan mungkin akan terus kujaga: menulis puisi. Yap, puisi yang tak lagi
melulu masalah cinta. Meski begitu tetap saja saya malu untuk
memperlihatkannya, kecuali orang-orang terdekat atau kuanggap dekat. Sementara ini,
cukuplah kutulis dan simpan sendiri coretan-coretan mungil itu. Puisi-puisi
gelap itu memberiku ketakutan jika pembacanya salah menafsirkan atau salah menangkap
maknanya sehingga memunculkan kecurigaan, permusuhan, atau pertikaian. Tak dipungkiri
saya pun berharap kelak ada yang membacanya, akan tetapi saat saya sudah tidak
di sana dan tak mengetahui jika ada yang membacanya.