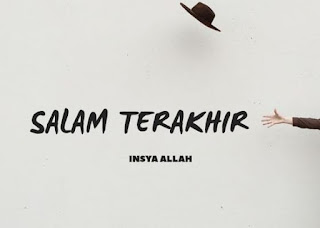Beberapa
waktu silam saya berdebat dengan teman tentang boba. Yah,
menurut lidahku boba atau pearl
terasa seperti makanan tradisional yang dijual di pasar-pasar, cetot. Oleh sebab
itu, saya menyadari sesuatu dan terpikirkan untuk menutup blog ini.
 |
| Cetot dan boba sumber perdebatan kami |
Terima
kasih kepada pembaca budiman yang mungkin tersesat dan bertemu blog ini. Terima kasih juga pada teman-teman yang menawarkan berbagai ide. Saya belum memiliki rencana-rencana itu. Tak mungkin karena cetot itu saya berhenti menulis karena saya sudah memiliki bekal: kehebatan tulisan yang ditentukan oleh kedalaman penderitaan. Well, meski sebagus-bagusnya kalimat tentu tak dapat mewakili hakikat.
Rencananya saya hendak menutup blog ini, namun urung kulakukan. Yah, siapa tahu di waktu-waktu mendatang Allah menggerakkan hatiku untuk kembali menulis di sini. Selain itu, lebih baik kubiarkan saja seperti ini sebagai jejak pemikiran sekaligus pengingat diriku di masa lalu. Pantengin saja status-status di medsosku, barangkali ada tulisan terbaruku di jurnal atau blog/web baru.
Rencananya saya hendak menutup blog ini, namun urung kulakukan. Yah, siapa tahu di waktu-waktu mendatang Allah menggerakkan hatiku untuk kembali menulis di sini. Selain itu, lebih baik kubiarkan saja seperti ini sebagai jejak pemikiran sekaligus pengingat diriku di masa lalu. Pantengin saja status-status di medsosku, barangkali ada tulisan terbaruku di jurnal atau blog/web baru.
2020
dan seterusnya adalah tahun-tahun penuh keriuhan. Gaungnya sudah mulai terasa
pada awal tahun lalu. Saya telah memikirkannya secara mendalam perihal
keputusan ini. Perlu kulepaskan beban tahun-tahun lampau dengan segala
konsekuensinya sambil terus menghadapi berbagai tantangan ke depan.
Pada
mula tahun ini ada hasrat untuk tak lagi menyiakan energi dan waktu. Di luar
sana masih banyak yang membutuhkan uluran tangan dan penyadaran. Masih banyak isu
atau wacana yang perlu dieksplorasi dan memerlukan perhatian lebih. Masih ada waktu, energi, dan kehidupan yang pantas untuk dicurahkan. Terlebih lagi, ternyata, ada yang bersedia berbagi beban. Saya patut bersyukur karena selama ini belum ada yang kuat dan mampu menahannya. Alhamdulillah.
Come on... Let’s go on JOURNEY!!!
Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia). (Ali Imran: 8)