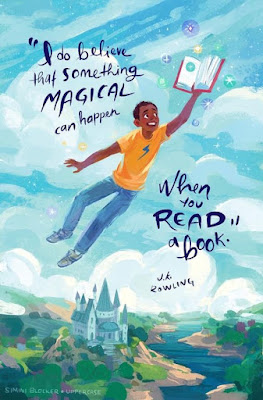 |
| thisscoop.com |
Tempo
hari saya bertemu mbak-mbak yang menjual buku-buku ayahnya. Seorang ayah
penggila buku dan bekerja dalam bidang jasa konstruksi. Semua buku itu,
katanya, untuk “sangu pensiun”. Kegilaannya membeli buku hingga memenuhi
rumahnya dan membuat sang istri marah. Anaknya pun menjual buku-buku sang ayah
satu per satu dengan harga second.
Sebagai
sesama pecinta buku, saya pun memahami alam pemikiran sang ayah. Sembari
membayangkan bagaimana keluargaku kelak dalam merespon hobiku tersebut. Ada
senyum tersungging saat mendengarkan penuturan si mbak-mbak. Saya bayangkan
jika kelak anakku menjual buku-bukuku tanpa sepengetahuanku. Tanpa Ia tahu
bahwa ayahnya ingin membuat perpustakaan mini untuk orang-orang di desa yang
jarang bersentuhan dengan buku.
Berhadapan
dengan orang yang tak suka buku sudah biasa kutemui. Tetapi, beruntunglah si
Mbak itu buku-buku ayahnya dijual kepadaku. Setidaknya, buku tersebut dapat
bermanfaat di tangan orang lain. Dan bersyukur juga saya karena mbak dan ibunya
tidak membakar buku-buku itu sehingga dapat saya beli.
Jangan
seolah-olah tak tahu jika ada pembakaran buku. Pertanyaan tersebut jikalau
engkau ajukan ke Fernando Baez akan dijawab bahwa pembakaran buku adalah salah
satu cara menghancurkan buku dan karena motif ideologi. Tesis Baez tersebut
barangkali meleset ketika melihat pengalaman pembakaran buku yang pernah
kualami. Tentu saja buku-bukuku pernah dibakar, bukan oleh pemerintah atau
aliran ekstremis tertentu melainkan oleh ayahku sendiri. Buku-buku saya dibakar
karena waktuku habis dengan membaca buku yang tidak berkaitan dengan pelajaran.
Lantas ayah membakarnya di belakang rumah agar saya berhenti membaca buku
selain buku pelajaran. Buku yang bermanfaat ialah buku pelajaran, mungkin
begitu kesimpulannya.
Terselip
rasa bahagia tatkala melihat orang lain membaca buku yang pernah kubaca. Biasanya
saya akan mengajak diskusi orang tersebut. Bahkan sampai ada yang mengejek, “jangan-jangan
cewek yang kau dekati itu kamu ajak juga membaca buku.” Ia tidak seratus persen
salah, ada benarnya juga sih. Lah memang seperti itulah saya biasanya mengawali
pembicaraan dengan lawan jenis. Mengawali dari obrolan yang kita suka to?
Dahulu saya
percaya bahwa ada semacam rasa solidaritas antar pembaca buku. Pada saat itu,
saya belum tahu bahwa ada banyak tipikal pembaca buku. Tak heran bila saya
dengan mudah meminjamkan buku kepada seseorang dengan rasa percaya bahwa dia
akan mengembalikannya. Bahkan sering pula kupinjamkan hingga sering saya
sendiri yang mengantar ke kosnya.
Saya lupa,
mungkin ada ratusan buku yang saya pinjamkan dan tak kembali. Kesadaran tersebut
muncul ketika menjalani akhir pekan pada masa awal-awal perkuliahan dahulu. Perlu
kalian ketahui bahwa tempat saya kuliah dulu, akhir pekan merupakan sebuah
kesunyian panjang yang menjemukan. Kampus menjadi sekumpulan gedung yang sangat
amat minim mahasiswa. Kawan-kawanku mayoritas pulang dan juga dengan mahasiswa
lainnya. Apa yang dilakukan mahasiswa pada saat akhir pekan di tengah kampus
yang dikepung sawah dan minim hiburan semacam mall atau hal-hal menyenangkan
lainnya? Tidak ada. Mereka tentu saja pulang karena rumah relatif dekat.
Saya? rumah
saya jauh. Pulang pun bisa satu semester sekali jika beruntung, jika buntung ya
tak pulang dalam setahun. Pada kondisi sunyi dan tak ada kawan bicara tersebut,
tiap awal bulan saya memborong buku untuk dibaca tiap akhir pekan. Hingga aku
sadar bahwa buku-buku tersebut entah lari kemana saja. Ada yang saya ingat
dipinjam oleh siapa dan terkadang lupa. Lebih menyebalkannya lagi ialah saya
memintanya dengan cara mengemis, bukan atas dasar kesadaran si peminjam
mengembalikan dengan sukarela.
Bagimu buku
merupakan hal sepele untuk dikembalikan, tetapi bagiku adalah hal yang lain. Bolehlah
engkau tak mengembalikan sandal, sepatu, baju atau yang lain. Saya sering
ikhlas jika itu yang diambil orang lain. Oh, kalau buku rasanya hampir menangis
jika tak kembali. Pernah suatu ketika ada yang nyeletuk,”Ah, Cuma buku saja
diributkan.” Tentu saja Ia tak memahami perjuanganku membeli buku. Tiap bulan
saya kerap menyisihkan uang makan untuk membelinya. Tiap akhir pekan ketika
yang lain pulang kampung, buku yang menemaniku. Saat yang lain malam mingguan
bersama pacar, buku yang menghiburku. Bahkan saat kawan-kawan yang lain sudah kelon dengan pasangannya, buku yang jadi
teman tidurku.
 |
| tapiture.com |
Ada juga
celotehan lain, “kalau hilang kan bisa beli lagi to.” Saya hanya mengelus dada.
Dia tak tahu perjuanganku memeroleh buku Arus Balik dengan membongkar sebuah
toko buku di jalan Semarang Surabaya. Saat ini carilah buku Arus Balik yang
asli (bukan bajakan) seharga lima puluh ribu. Engkau tak akan menemukannya,
kecuali seharga ratusan ribu bahkan jutaan. Atau seberapa sadar mereka bahwa
buku Cerita Dari Blora seharga setengah dari uang bulananmu. Atau apakah engkau
bisa menemukan novel Seratus Tahun Kesunyian karya Gabo yang asli dibawah
seratus ribu? Tidak, kau akan sulit menemukannya alih-alih justru tak
menemukannya. Meskipun kau temukan yang ori, terkadang sulit untuk menebusnya
karena kau tak selalu memiliki uang.

.png)






No comments:
Post a Comment