Nama
Buku : AYAH
Penulis : Andrea Hirata
Penerbit : Bentang
Cetakan : Pertama, 2015
Tebal : xx+412 halaman
Wahai awan
Kalau bersedih
Jangan menangis
Janganlah turunkan
hujan
Karena aku mau pulang
Untukmu awan
Kan kuterbangkan
layang-layang…
Di
kala Bulan Ramadhan kutulis sesuatu yang kuanggap resensi ini pada malam hari. Jika
ditulis siang hari tak ada rokok yang menemani. Tentunya para jomblowan dan
jomblowati mengerti rasanya sendiri. Di tengah deadline tesis yang kian
mencekik dan daripada siang hari tidur pulas atau tak bisa tidur kembali,
akhirnya kuputuskan untuk membaca novel ini. Meskipun pada mulanya ‘sang malam’
mengatakan bagus, namun kisahnya sensitif. Benakku bertanya-tanya, apanya yang
membuat sensitif? Apakah novel ini berkisah tentang ayah yang berpoligami? Atau
tentang kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh si ayah? Dan seperti
biasanya ‘sang malam’ dan dia memang selalu begitu. Dia yang suka membuatku
bertanya-tanya.
Ini
novel kedelapan karya Andrea yang kubaca setelah tetralogi laskar pelangi,
dwilogi Padang Bulan, dan Sebelas Patriot (yang tipis itu). Puzzle. Seperti itulah
Andrea menyusun kisahnya layaknya puzzle yang bertebaran tak beraturan dengan
bab-bab kemudian semakin jelas dan terang di menjelang akhir. Tak lupa menjadi
kebiasaan sang penulis menyisipkan karakter dan kisah jenaka dalam ceritanya. Pendalaman
karakter dan kebiasaan masyarakat Belitong dan sekitarnya menjadi keunggulan
Andrea. Terutama tema kawin-cerai yang hari ini kian marak tak luput dari
pengamatan. Novel ini tidak melulu tentang Ayah, lebih dari itu, ini kisah
tentang menjadi ayah dan anak, perjuangan cita dan cinta, keputusasaan, persahabatan,
harapan dan kebangkitan. Saya mahfum ketika sang malam bilang ini sensitif
karena ada cerita tentang perjuangan cinta di kala SMA (hohoho…). Ternyata masih
cemburu jua dikau. Padahal sudah tiga tahun lalu engkau membaca cerpen itu. Tenang,
ada kok kisah tentang dirimu yang masih mengendap di kepala ini. Tinggal nunggu
mood saja (munculin mood itu yang susah hehehe).
Kisah
sentralnya adalah Sabari yang sabar meski cintanya bertepuk sebelah tangan. Ia sangat
terinspirasi oleh karya Gabo “Love in the Time of Cholera”. Saya mengira kisah akan
berakhir seperti pernikahan Florentina Ariza dan Fermina Daza setelah menunggu lebih
dari setengah abad. Namun, nyatanya tidak karena ini karya Andrea bukan Gabo
jadi lebih realistis. Zorro meskipun bukan anak biologis Sabari, tetapi Ia
membesarkan dengan rasa cinta dan ketulusan seoarang Ayah (pada fase ini jadi
inget lagu Angge-Angge Orong-Orong). Zorro
yang dibesarkan dengan kasih sayang, cinta dan puisi oleh Sabari menjadi anak
yang halus budi pekertinya. Apalagi Zorro pun juga pintar bersyair seperti Sabari. Salah satu puisi Rayuan Awan mungkin yang menurutku mengena. Yah, meskipun saat ini layang-layang tidak terlalu populis karena semakin minimnya tanah lapang dan kerap menjadi penyebab mati listrik (sering menghiasi kabel-kabel listrik dan telepon). Suatu pembelajaran bagaimana mendidik seoarang
anak. Lantas ada kisah Ukun dan Tamat sebagai kawan yang pontang-panting
keliling Sumatra mencari Ibu dan anak yang membuat kawannya menjadi gila. Semangat
Izmi dan keluguan Amirza yang menambah ruh novel. Dan pembelajaran paling
penting dari novel ini adalah tak selamanya penyair mendapatkan cinta yang dia
inginkan atau mungkin Sabari kurang mempergunakan syairnya untuk menggombal
hehehe… Pesanku, “Sabari, engkau perlu belajar pada Dilan.”
Sudah
ah. Sekian dulu. Waktu refreshing sudah lewat. Sekarang memasuki waktu mengetik
tesis. 
.png)
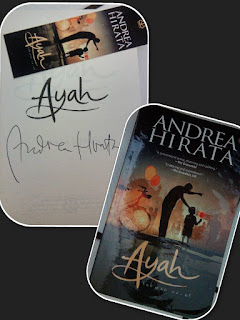






No comments:
Post a Comment